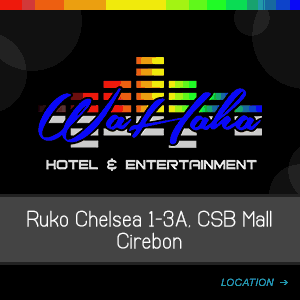KONTROVERSI HUKUMAN MATI
Amroji melipat sajadah lusuhnya sehabis menunaikan sholat isya di musholah kecil di lapas Nusakambangan. Sholatnya tadi begitu khusyuk, nikmat sekali ia rasakan. Itu bukan sholat isya biasa baginya. Itu adalah sholat isya terakhir di dunia, sebelum ia menghadap pada Yang Maha Kuasa. Beberapa jam lagi ia akan menjalani hukuman mati. Suatu jalan syahid yang ia yakini dapat mengantarnya menuju Sang Khalik.
Sejak ia bangun subuh tadi semua terasa berbeda. Istimewa. Ini bukan hari yang biasa untuknya. Nafasnya lega memburu udara. Aliran darah sungguh terasa hangat menjalar ke sekujur tubuhnya. Setiap hembusan angin begitu semilir ia rasakan menumbuk tubuhnya, ia merasa seperti dibelai. Duhai hidup, sisa beberapa jam terakhir ini sungguh hal yang luar biasa. Amroji begitu tenang dan ikhlas menjalani nasibnya menyongsong maut.
Amroji hanya satu dari sekian banyak orang dibalik jeruji yang dijatuhi hukuman mati. Perbuatannya yang merenggut nyawa orang banyak dinilai layak diganjar hukuman mati. Sederhananya, nyawa dibayar nyawa. Tapi benarkah se-sederhana itu?
Setiap tahun ada ribuan orang menjalani vonis hukuman mati di seluruh dunia. 94% praktik tersebut berlaku di Iran, Arab Saudi, Tiongkok dan Amerika Serikat. Majelis Umum PBB katanya pernah mengeluarkan resolusi tidak mengikat mengenai penghapusan hukuman mati sejak 2007 hingga 2014. Meskipun karena itu hasilnya adalah hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, namun sekitar 60% penduduk dunia nyatanya bermukim di negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati tersebut. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati.
Lalu apa sebenarnya tujuan dari pemberlakuan praktik hukuman mati itu? Efek jera.
Ampuhkah? Tidak.
Beberapa studi ilmiah tidak berhasil menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa hukuman mati berhasil memberi efek jera dan efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Bahkan survei yang dilakukan PBB tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada kasus pidana pembunuhan.
Lalu apa hubungan yang jelas dengan angka tindak kriminal pembunuhan?
Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Itu faktanya!
Praktik hukuman mati juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan. Hukuman mati diyakini kerap kali tercampur dengan urusan politik di berbagai negara.
Pada dasarnya, praktek hukuman mati dimaksudkan untuk memelihara kehidupan yang lebih luas. Misalkan bila seorang terpidana pembunuh dipenjara, dia akan mungkin jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi setelah keluar dari masa hukuman. Tetapi yang jadi masalah, dia juga masih mungkin akan melakukan kejahatan pembunuhan lagi selepas dari penjara. Ini yang terjadi dengan residivis kambuhan. Artinya, dia si pelaku kejahatan tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat luas. Sedangkan kalau dia dihukum mati, maka dia tidak berkesempatan mengulangi perbuatannya. Kalau benar begitu adanya, tidak cukup kah dengan hukuman penjara seumur hidup?
Prinsip pemikiran diatas adalah “si pembunuh jangan diberi kesempatan mengulangi perbuatannya.”
Tapi yang terlupakan dari dasar pemikiran itu adalah; “si pembunuh juga tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya.”
Lebih jauh lagi, “si pembunuh tidak diberi kesempatan hidup.”
Lalu standard pemberian kesempatan hidup itu siapa yang layak terbitkan? Manusia?
Misalkan goal yang dimau adalah keadilan. Lalu adil bagi siapa? Buat korban? Dengan hukuman matipun, sepertinya tetap tidak sepadan dengan kehilangan atau kerugian yang diderita si korban. Saya coba analogikan nilai adil tersebut kedalam dua asas, kualitas dan kuantitas.
Pertama, asas kualitas. Misalkan si kriminal membunuh seorang suami dari seorang wanita. Lalu untuk memberikan rasa adil bagi wanita tersebut, si pelaku dibunuh juga. Apa hal tersebut telah seimbang? Sudah adilkah bagi wanita tersebut? Apa yang diderita oleh wanita itu? Kehilangan. Apa kerugian wanita itu terbayar dengan menghukum mati si pembunuh tersebut? Jawabannya pasti tidak.
Kedua, asas kuantitas. Misalkan si kriminal membunuh 50 orang dengan bom. Lalu pelaku pembunuhan itu dihukum pancung. Yang terjadi adalah 50 nyawa dibayar hanya dengan 1 nyawa. Sudah adil? Jawab sendiri.
Kalau memang hukuman mati tidak mengurangi kriminalitas, kenapa masih diterapkan? Negara repot mengurus narapidana yang jumlahnya dikhawatirkan semakin banyak? Jadi daripada repot ngurus napi, hukum mati aja gitu? Loh, bukannya negara justru seharusnya repot ngurus kualitas pendidikan dan aparatur hukum serta taraf kesejahteraan ya? Kalau repotnya fokus dan benar di bagian ini, negara ngga perlu khawatir dengan peningkatan angka kriminalitas kok!
Sebagai penutup, mari kita kembali ke dasar. Apa definisi kata pembunuh? Ia adalah orang yang menghilangkan nyawa makhluk (manusia) lainnya dengan sengaja, atau merampas hak hidup manusia lainnya dengan paksa. Lalu dalam konteks pelaku vonis hukuman mati, apakah yang menjalankan hukuman mati itu tidak juga bisa dikatakan sebagai pembunuh?
Tindak kriminal pembunuhan itu memang keji, bandar narkoba itu memang super jahat, pelaku teror itu jelas bukan kejahatan kecil. Tapi sudah benarkah dengan membunuh mereka? Kiranya kita tahu bahwa kebaikan tidak terlahir dengan cara dan perbuatan yang salah. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah membunuh itu cara yang benar?